Judul Buku : Anak Lumpur Menggapai Matahari
Penulis : K.H. Junaedi al-Baghdadi
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Tebal : 192 Halaman
Cetakan : Pertama, 2014
ISBN : 978-602-03-0353-6
AWALNYA judul buku ini menjawil perhatian, ketika
saya melongok sejumlah bacaan yang tertata rapi pada rak dengan cap ”Buku Baru”
di salah satu toko buku favorit di Surabaya, tahun kemarin. Utamanya lantaran
terselip kata ”lumpur” dalam rangkaian titelnya. Seketika pikiran teringat
masalah lumpur Lapindo yang seakan tak kunjung beres, kesannya timbul-tenggelam
hanya sebagai pemberitaan media selama ini. Kabar paling buncit menjelang
pemerintahan SBY lengser, pemerintah yang bakal menanggung sisa ganti rugi oleh
perusahaan Bakrie itu.
Terpikirkan karya ini mengisahkan sekelumit nestapa
berkepanjangan yang mungkin dialami penulisnya, selaku bagian korban semburan
lumpur yang memang kerap memantik keprihatinan banyak pihak yang masih waras.
Apalagi, tertulis pengarangnya berpredikat kiai, lengkap dengan gambar sosoknya
yang bersahaja di sampul luar. Sementara, dulu sempat beredar kabar dari mulut
ke mulut, lumpur Lapindo juga menenggelamkan pesantren binaan seorang kiai
berpengaruh, serta masjid kuno peninggalan zaman Londo di sekitarnya.
Imbuhan stiker bercorak medali bertera ”Rekor MURI
Buku dengan Harga Jual Tertinggi Saat Launching” yang menghiasi cover
pustaka ini, semakin menggelitik rasa ingin tahu. Mengingat, tak sedikit
literatur yang bandrolnya sampai mendekati angka dengan lima nol belakang, saat
dilepas ke pasaran terdahulu. Karena itu, akhirnya saya menyangkingnya pulang,
guna menemukan jawaban atas gejolak penasaran. Tentu usai saya membayarnya
dengan potongan dua puluh persen di kasir.
Kala mulai menyingkap awal-awal lembarannya, kisah
yang tertoreh sedikit berbeda. Rupanya cerita yang tersaji di dalamnya,
samasekali tidak berhubungan dengan muntahan lumpur di Porong bertahun-tahun
terakhir. Melainkan, frase ”lumpur” yang dimaksud hanyalah tanah becek galibnya
sehabis turun hujan deras. Kosakata aslinya ”cellot” yang sudah jamak
dalam rumpun bahasa Madura pada umumnya. Bagian habitat yang melingkupi warga
udik. Oalaaah...
Walau begitu, dugaan saya tidak meleset sepenuhnya. Buku
ini menyampaikan liku-liku kehidupan lampau penulisnya yang memang seringkali
berlumur lumpur. Baik dalam arti denotasi maupun konotasinya. Tepatnya ketika
masa kecil si empu hikayat senantiasa berbecek ria dalam lumpur sawah. Dengan
secercah percaya yang tak pernah lekang, ia pun tak kenal payah terus berupaya
mentas dari kubangan lumpur kemiskinan yang serasa membelit setiap langkahnya.
Membaca novel biografi setebal dua ratusan halaman
ini, akan membangkitkan ingatan kembali pada dinamika sosial wilayah pedalaman.
Khususnya daerah tapal kuda, Jawa Timur, sebelum abad milenium. Waktu itu,
kehidupan sebagian besar masyarakatnya jeblok di bawah taraf kesejahteraan.
Upaya pemenuhan kebutuhan dasar juga cenderung selalu mengandalkan cara-cara
amat tradisional. Infrastruktur semisal listrik pun belum ternikmati, hanya
lampu teplok yang setia menemani berbagi terang di setiap rumah.
Fakta macam itu menimpa pula kebanyakan lapisan
sosial akar rumput dusun Krasak, desa Ajung, kecamatan Jenggawah, kabupaten
Jember; tempat kelahiran si penulis. Ia sendiri terlahir dan besar dalam
keluarga yang serbakekurangan materi. Ayahnya hanya buruh tani, sedangkan
ibunya buruh gudang tembakau. Itu pun tak ubahnya pekerjaan musiman. Bisa
dibayangkan penghasilan orangtuanya sangat tidak memadahi, untuk sekadar
memenuhi kebutuhan pokok berikut keperluan sekolahnya. Meski dirinya anak
semata wayang.
Rumahnya boleh dibilang jauh dari kesan nyaman. Asupan
pangannya tidak mencerminkan standar kesehatan. Ia bersama ayah-ibunya kerap
makan hanya dengan nasi berlauk-pauk sambal (lazimnya garam dan cabe rawit
belaka). Ia juga tak jarang makan di rumah kerabatnya yang kondisi ekonominya
sedikit lebih baik. Apalagi, sandangnya termasuk seragam belajarnya terkesan
ala kadarnya. Ia sempat ditegur gurunya karena tidak memakai sepatu ke sekolah.
Jumaadi demikian namanya sewaktu kanak-kanak, bahkan
ikut berupaya mencari penghasilan sendiri, guna meringankan beban orangtuanya
yang menurutnya sudah menderita bukan kepalang. Mulai dari ikhtiarnya berjualan
es lilin keliling, menjajakan jemblem dagangan bibinya, hingga menjual biji
pinang sebagai persiapan meneruskan pendidikannya setamat jenjang SD nanti. Ia
pun tidak gengsi mengikuti ibunya ngasak (memulung) butiran padi sisa
panen di sawah milik orang-orang agar bisa tetap makan.
Namun, ia pantang menyerah. Apapun deraan kesulitan
yang dahsyat membelit diri beserta keluarganya, ia tetap yakin bahwa Tuhan
pasti akan meluangkan kesempatan baginya untuk meraih impian. Sebagaimana
ayahnya sering mencurahkan wejangan berimbuh teladan sikap tawakal. Bukan
sebatas pasrah bongkokan. Ditambah tempaan character building dan
spiritualitas keagamaan dari para gurunya. Pada gilirannya, ia senantiasa
melakoni titian nasib zaman bocahnya dengan penuh keikhlasan tanpa mengeluh.
Dari sini, torehan pena ini serasa hendak pula
mengingatkan kembali tentang spirit otentik wong ndeso, sekaligus
karakteristik penduduk Nusantara yang seolah kian pudar tergerus modernitas
hedon. Semangat yang bersumber dari kesadaran total, betapa segala kekurangan
(ekonomi) bukanlah alasan untuk memupus harapan kegemilangan esok.
Gelora embusan keyakinan yang lantas mengejewantah
pula dalam tindakan, bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Optimisme
mengenai keberhasilan bukan monopoli segelintir orang, tapi hak siapa pun yang
berkemauan. Sementara, ketika telah mencapai kesuksesan, tetap rendah hati
terhadap sesama dengan mengedepankan kebersahajaan.
Rerata wong ndeso terutama sepanjang kurun
latar tempo kisah dalam buku ini, dikenal sebagai kaum pekerja keras. Hampir
setiap waktu yang tersedia, mereka nikmati untuk makaryo segenap daya.
Bagi mereka, hidup adalah perjuangan disertai pengabdian yang tulus, ke arah
terwujudnya mimpi dan kebahagiaan hakiki. Tak semata asa dan ketenteraman
pribadi, namun juga cita-cita dan kesentosaan bersama. Kendati hanya dengan
sarana maupun prasarana seadanya, bahkan tanpa ditopang fasilitas apapun.
Seperti motto yang melekat pada jatidiri Om Dahlan Iskan dan kemudian
menjadi jargon pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sekarang. Kerja kerja
kerja...
Lebih dari itu, wong ndeso secara umum
aslinya dikaruniai potensi unik dalam mengatasi kesumpekan. Di antaranya,
selera humor yang maknyus. Mereka selalu punya cara tersendiri melumerkan
kebuntuan, tanpa harus terlalu beringsang larut dalam kekalutan yang hanya akan
menghilangkan keceriaan. Justru mereka begitu enjoy menyikapi
keterbatasan sebagai bahan menertawakan diri sendiri. Tak heran, bila lantas
mereka cenderung ditandai keteguhan lelaku yang berbalut kesederhanaan,
ketulusan, dan keikhlasan.
Gambaran demikian kiranya bisa diresapi pada gaya
penulisan novel ini yang sengaja disajikan apa adanya. Pengisahannya begitu
mengalir sesuai dengan karakteristik masing-masing tokohnya, membersitkan
kepolosan warga perkampungan terpencil, serta dunia kanak-kanak. Bahkan, sempat
dikisahkan cuplikan insiden berantem lazimnya para bocah yang menggelikan,
dengan penyelesaian yang tak kalah mengocok perut.
Jauh lebih menghibur ketimbang perselisihan di
antara wakil rakyat sejauh ini. Serangkaian dialognya juga nyaris masih
bercitarasa Madura yang di-Indonesia-kan. Para sedulur yang belum
terbiasa menyesap sajian literasi model begini, bisa jadi merasa monoton dan
kudu pelan-pelan selama menyimaknya. Namun, dengan begitu cetusan pengalaman
ini justru benar-benar akan dinikmati pembaca hingga tuntas.
Selebihnya, perlu disyukuri ketika semakin
bermunculan para figur teladan, yang berani mengambil pilihan tetap
memertahankan spirit otentik wong ndeso di abad kekinian. Mereka yang
selain telah membuktikan guratan prestasi dan raihan kesuksesan hari ini, juga
ikut urun mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara. Berbekal tekad
menggapai matahari bekerja keras dan cerdas, menggiatkan perubahan menemu
pencerahan.
Laksana petikan syair lagu Suci dalam Debu besutan musisi asal
negeri Jiran era 90an, yang dikutip pula dalam buku nyentrik ini beberapa kali:
debu jadi permata, hina jadi mulia. Sama halnya dengan penulisnya yang semula
hanya ”anak lumpur”, kemudian berganti predikat KH Junaedi al-Baghdadi yang
berbagi inspirasi dan berkhidmat sebagai Pengasuh Pesantren Al-Baghdadi di
Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, kini.
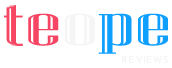






0 komentar :
Posting Komentar